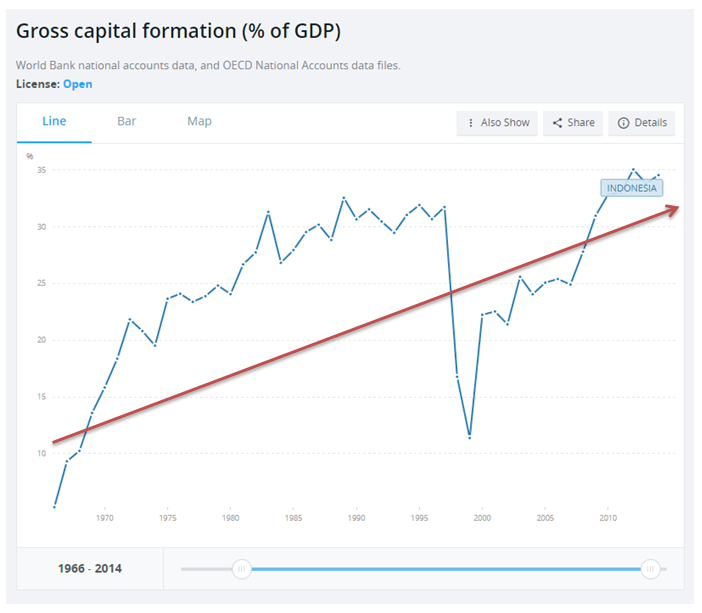Oleh : Friedrich Engels
Dicopy
dari : http://www.marxists.org/indonesia/archive/marx-engels/1881/klas.htm
Telah sering dipertanyakan, hingga seberapa jauh
berbagai klas masyarakat itu berguna atau bahkan diperlukan? Dan dengan
sendirinya jawabannya berbeda untuk setiap kurun sejarah yang dipersoalkan. Tak
disangsikan lagi telah pernah ada masa ketika suatu aristokrasi teritorial
merupakan suatu unsur masyarakat yang tak terelakan dan diperlukan. Namun itu,
adalah dulu sekali, lama berselang. Ada suatu masa ketika suatu klas kapitalis
menengah, suatu burjuasi seperti yang orang Perancis menyebutkannya, lahir
dengan keharusan yang sama tidak terelakannya, yang berjuang terhadap
aristokrasi teritorial itu, yang mematahkan kekuasaan politiknya, dan pada
gilirannya menjadi predominan secara ekonomik dan politik. Tetapi, sejak
lahirnya klas-klas, tidak pernah ada suatu zaman di mana masyarakat dapat tanpa
suatu klas pekerja. Nama, status sosial dari klas itu telah berubah; para hamba-sahaya
telah menggantikan para budak, untuk pada gilirannya digantikan oleh orang
pekerja bebas-bebas dari perhambaan tetapi juga bebas dari semua pemilikan
keduniaan kecuali tenaga kerjanya sendiri. Tetapi teramat jelas: perubahan
apapun yang terjadi pada lapisan-lapisan atas masyarakat, yang
tidak-memproduksi (non-producing), masyarakat tidak dapat hidup tanpa
suatu klas penghasil/produser. Maka klas inilah yang diperlukan dalam semuas
keadaan-walaupun waktunya mesti tiba, ketika ia tidak merupakan suatu klas
lagi, ketika ia menjadi (merupakan) seluruh masyarakat.
Nah, keharusan apakah yang ada dewasa ini bagi
keberadaan setiap dari ketiga klas ini?
Aristokrasi bertanah, boleh dikatakan, secara
ekonomik tidaklah berguna di Inggris, sedang di Irlandia dan Skotlandia ia
telah menjadi suatu gangguan positif dikarenakan kecenderungan-kecenderungan
depopulatifnya. Mengirim orang menyeberangi samudera atau ke dalam kelaparan,
dan menggantikan mereka dengan domba atau kijang-itu saja kegunaan yang dapat
diklaim oleh para tuan-tanah Irlandia dan Skotlandia. Coba biarkan persaingan
makanan sayur-sayuran dan hewani Amerika berkembang lebih maju lagi, dan kaum
aristokrasi bertanah Inggris akan melakukan hal yang sama, paling tidak mereka
yang mampu berbuat begitu, karena mempunyai estate-estate (tanah
berukuran luas) kota sebagai andalannya. Untuk selebihnya, persaingan makanan
Amerika akan segera membebaskan kita. Dan ini yang semujur-mujurnya-karena
tindak-politik mereka, baik di Majelis Tinggi dan di Majelis Rendah, sungguh
suatu gangguan nasional yang paling puncak.
Tetapi, bagaimana dengan klas kapitalis menengah
itu, klas yang telah dicerahkan dan liberal, yang membangun imperium kolonial
Inggris dan yang memantapkan kemerdekaan Inggris? Klas yang telah mereformasi
parlemen di tahun 1831, membatalkan Undang-undang Gandum dan menurunkan pajak
demi pajak? Klas yang menciptakan dan masih mengarahkan manufaktur-manufaktur
raksasa, angkatan laut perdagangan yang luar-biasa besarnya, dan sistem
perkereta-apian Inggris yang terus meluas? Jelaslah klas itu setidak-tidaknya
adalah sama diperlukan seperti klas pekerja yang dikendalikan dan dipimpinnya
dari kemajuan ke kemajuan.
Memang, fungsi ekonomik klas menengah kapitalis itu
adalah menciptakan sistem modern manufaktur dengan tenaga (mesin) uap dan
komunikasi bertenaga uap, dan menghancurkan setiap hambatan ekonomik dan
politik yang menunda atau menghalangi perkembangan sistem itu. Tidak
disangsikan lagi, selama klas menengah kapitalis menjalankan fungsi ini, dalam
keadaan-keadaan seperti itu, ia adalah suatu klas yang diperlukan. Tetapi,
masihkah keadaannya seperti itu? Adakah ia masih memenuhi fungsi dasar sebagai
pengelola dan penuai produksi sosial bagi keuntungan masyarakat seluruhnya?
Mari kita periksa.
Kita mulai dengan alat-alat komunikasi. Dan kita
dapati telegrafi berada di tangan pemerintah. Perkereta-apian dan sebagian
besar kapal-kapal uap samudera dimiliki, bukan oleh kapitalis-kapitalis
individual yang mengelola bisnis mereka sendiri, melainkan dimiliki oleh perusahaan-perusahaan
perseroan yang bisnisnya dikelola untuk mereka oleh pegawai-pegawai bayaran,
oleh pegawai-pegawai yang kedudukannya sepenuh dan selengkapnya adalah sebagai
pekerja-pekerja atasan dan yang dibayar lebih baik. Sedangkan yang mengenai para
direktur dan pemegang saham, mereka mengetahui bahwa semakin sedikit yang
tersebut duluan mencampuri manajemen, dan yang tersebut belakangan dengan
supervisi/pemilikan, semakin baiklah itu bagi perseroan tersebut. Suatu
pengawasan yang longgar dan cuma resminya saja memang merupakan satu-satunya
fungsi yang tersisa bagi para pemilik bisnis itu. Dengan demikian kita melihat
bahwa sesungguhnya para pemilik kapitalis perusahaan-perusahaan raksasa ini
tidak mempunyai kegiatan lain dalam perusahaan-perusahaan itu kecuali menerima
dividen-dividen (pembagian keuntungan) setengah-tahunan. Di sini fungsi sosial
para kapitalis telah dialihkan pada pegawai-pegawai yang dibayar dengan upah;
sedangkan ia sendiri terus mengantongi, dengan dividen-dividen itu, upah untuk
fungsi-fungsi itu, sekalipun ia telah berhenti mengerjakannya.
Tetapi sebuah fungsi lain masih tersisa bagi kaum
kapitalis itu, yang telah dipaksa "pensiun" dari manajemen karena
luasnya perusahaan-perusahaan raksasa bersangkutan. Dan fungsi ini ialah berspekulasi
dengan saham-sahamnya di pasar bursa. Karena tiada sesuatu untuk dikerjakan,
maka para "pensiunan" kita itu, atau yang sesungguhnya para kapitalis
yang digantikan itu, berjudi sesuka-suka hati mereka di lingkungan gemah-ripah
ini. Mereka pergi ke sana dengan niat tegas untuk mengantongi uang yang
pura-pura mereka peroleh (sebagai 'upah') sekalipun mereka mengatakan, bahwa
asal-muasal segala pemilikan adalah kerja dan simpanan-barangkali memang
asal-muasalnya, tetap jelas bukan tujuannya. Betapa munafiknya: dengan
kekerasan menutup rumah-rumah judi yang kecil-kecil, sedangkan masyarakat
kapitalis kita tidak dapat hidup tanpa sebuah rumah judi raksasa, di mana
berjuta-juta demi berjuta-juta diderita sebagai kekalahan dan dimenangkan,
menjadi pusat masyarakat itu sendiri! Di sini, sesungguhnya, keberadaan para
kapitalis pemegang saham yang "pensiun" itu tidak hanya menjadi
berlebihan, melainkan juga suatu gangguan yang tiada terhingga.
Kenyataan yang sebenarnya dalam perkereta-apian dan
perkapalan-uap hari demi hari kian menjadi kenyataan pula bagi semua perusahaan
manufaktur besar dan perdagangan. "Pengambangan"-mengubah
kongsi-kongsi perseorangan besar menjadi perseroan-perseroan terbatas-telah
menjadi kenyataan selama lebih dari sepuluh tahun terakhir. Dari
pergudangan-pergudangan kota Manchester hingga bengkel-bengkel dan
tambang-tambang batubara di Wales dan di Utara dan pabrik-pabrik Lancashire,
segala sesuatu sedang atau telah dibuat mengambang. Di seluruh Oldham nyaris
tersisa sebuah pabrik katun yang berada di tangan perseorangan; bahkan pedagang
eceran semakin digantikan oleh 'toko-toko koperatif,' yang sebagian terbesarnya
hanyalah koperasi dalam nama belaka-tetapi mengenai ini kita tunda untuk lain
kali. Demikianlah telah kita melihat bahwa oleh perkembangan sistem produksi
kapitalis itu sendiri, kaum kapitalis digantikan secara sama seperti
pemintal-tangan. Tetapi dengan perbedaan, bahwa pemintal-tangan ditakdirkan
pelan-pelan mati-kelaparan, dan kapitalis yang digantikan itu dengan kematian pelahan-lahan
karena terlampau banyak makan. Dalam hal ini mereka umumnya sama saja:
kedua-duanya tidak mengetahui harus bagaimana diri mereka itu.
Maka, inilah hasilnya: perkembangan ekonomik
masyarakat aktual kita semakin cenderung berkonsentrasi, mengsosialisasikan
produksi ke dalam perusahaan-perusahaan raksasa yang tidak dapat lagi dikelola
oleh kaum kapitalis tunggal. Segala omong-kosong mengenai "ketajaman
melihat", dan keajaiban-keajaiban yang dihasilkannya, berubah menjadi
omong-kosong besar segera setelah suatu perusahaan mencapai suatu ukuran
tertentu. Bayangkanlah "ketajaman melihat" Perkereta-apian London dan
Barat-laut! Tetapi, yang tidak dapat dikerjakan oleh sang majikan/ahli, pekerja
biasa, hamba-hamba perusahaan yang berupah, dapat melakukannya dan itupun
dengan berhasil.
Demikianlah, kaum kapitalis tidak dapat lagi
mengklaim keuntungan-keuntungan/laba sebagai "upah
pengawasan/supervisi," karena ia tidak mengsupervisi apapun. Biarlah
selalu kita ingat itu, manakala para pembela modal menggembar-gemborkan kalimat
itu.
Tetapi, dalam nomor minggu lalu, telah kita coba
buktikan bahwa klas kapitalis juga menjadi tidak mampu mengelola sistem
produktif rakasa negeri ini; bahwa di satu pihak mereka telah memperluas
produksi sehingga secara berkala membanjiri seluruh pasar dengan produk-produk,
dan di lain pihak menjadi semakin tidak mampu mempertahankan diri terhadap
persaingan dari luar (negeri). Demikianlah kita mendapati, bahwa kita tidak
saja dapat dengan sangat baik mengelola industri-industri besar negeri ini
tanpa campur-tangan klas kapitalis , tetapi juga, bahwa campur-tangan mereka
itu semakin menjadi gangguan tak-terhingga.